“Saya lebih suka melihat koperasi berkembang daripada seribu orang kaya.”
— Bung Hatta
Tulang Bawang, 12 Agustus 2025. Ada
yang bilang, hidup itu soal meninggalkan jejak. Tapi Bung Hatta… seolah-olah
justru berusaha tidak meninggalkan apa-apa — kecuali nilai-nilai yang
dalam, sunyi, dan menempel di hati orang yang pernah mengenalnya.
Hari
ini, 12 Agustus, kita memperingati ulang tahun pria itu. Lahir di Bukittinggi,
1902. Seorang cendekia, proklamator, wakil presiden, dan… satu gelar yang
mungkin paling pas menggambarkan laku hidupnya: Bapak Koperasi Indonesia.
Tapi
kalau kita bicara Bung Hatta cuma dari gelarnya, dari sejarah politik, atau
dari fotonya yang diam berdiri di samping Soekarno — kita bakal melewatkan
banyak hal. Karena sesungguhnya, Bung Hatta itu lebih dari sekadar tokoh. Beliau adalah teladan hidup yang berjalan dengan kepala tegak dan hati yang
tenang.

Sepatu Bally, dan Kesederhanaan yang
Menyesakkan
Pernah
dengar kisah sepatu Bally?
Bung Hatta muda, waktu belajar di Belanda, terpikat sekali dengan sepatu buatan Swiss itu. Tapi harganya tidak main-main. Dia tahan. Dia pikir, nanti saja, kalau sudah mapan. Lalu waktu berlalu. Dia jadi wakil presiden. Tapi... sepatu itu masih belum dibeli. Bukan karena dia tidak bisa. Tapi karena dia tidak mau. Ia merasa, memakai uang negara buat beli barang mewah bukan haknya. Walau cuma sepasang sepatu.
Setelah Bung Hatta wafat pada 14 Maret
1980, keluarga menemukan selembar guntingan iklan koran tentang sepatu merek
Bally yang tersimpan rapi di dalam dompetnya. Iklan tersebut menjadi "saksi
bisu" dari kerinduan sederhana beliau terhadap sepatu impian yang tak
sempat dibeli hingga akhir hayatnya—meski secara posisi, beliau sebenarnya bisa
saja membelinya dengan mudah.
Dan
yang bikin kisah ini makin perih?
Konon
menurut sejumlah kisah yang beredar sepatu itu akhirnya datang. Warnanya hitam
mengkilap, elegan, merek Bally. Sepatu yang sama—atau paling tidak mirip—dengan
yang Bung Hatta pernah impikan puluhan tahun lalu. Tapi ia tak sempat
mencobanya. Sepatu itu tiba di rumah ketika Bung Hatta sudah terbujur
kaku. Ia wafat dalam kesederhanaan, dalam diam, tanpa riuh sorotan. Sepatu itu
diletakkan di samping jenazahnya—bukan untuk dikenakan, melainkan untuk menebus
sebuah janji yang tak pernah sempat ditepati: janji pada diri sendiri bahwa
kelak, jika mampu, ia akan membelinya. Anak-anaknya baru bisa membelikan
sepatu Bally itu setelah beliau wafat. Sepasang sepatu yang akhirnya
diletakkan diam di samping jenazahnya. Tak pernah dipakai. Tak pernah
diinjakkan ke tanah.
Bung Hatta: Harga Diri yang Tak
Pernah Padam
Bung Hatta tidak hidup dari jabatan. Setelah tidak lagi di pemerintahan, beliau tidak mendirikan partai, tidak membangun bisnis besar, tidak melobi siapa-siapa. Yang dilakukannya? Beliau menulis. Duduk di ruang kerja kecil. Menulis buku. Untuk dijual. Untuk makan. Sahabat, kita bicara tentang seorang mantan wakil presiden. Proklamator. Tapi dia memilih hidup dari pikirannya sendiri, bukan dari koneksi atau nostalgia kekuasaan.
Suatu hari, listrik di rumah Bung Hatta diputus. Bukan karena beliau tak
peduli, tapi karena memang tak ada uang untuk membayar tagihan. Bagi banyak
orang, mungkin mudah saja meminta bantuan atau memanfaatkan jabatan. Tapi tidak
bagi Hatta. Sejak muda, ia memilih hidup sederhana dan menolak segala bentuk
keuntungan pribadi dari kekuasaan. Dalam sebuah surat, ia pernah menulis, “Saya
tidak punya apa-apa. Tapi saya punya harga diri.”
Bagi
Hatta, harga diri itu seperti listrik sejati dalam hidup—memberi cahaya yang
tak akan pernah padam, sekalipun lampu di rumahnya mati. Nilai inilah yang
mengalir ke seluruh pemikiran beliau, termasuk tentang koperasi.
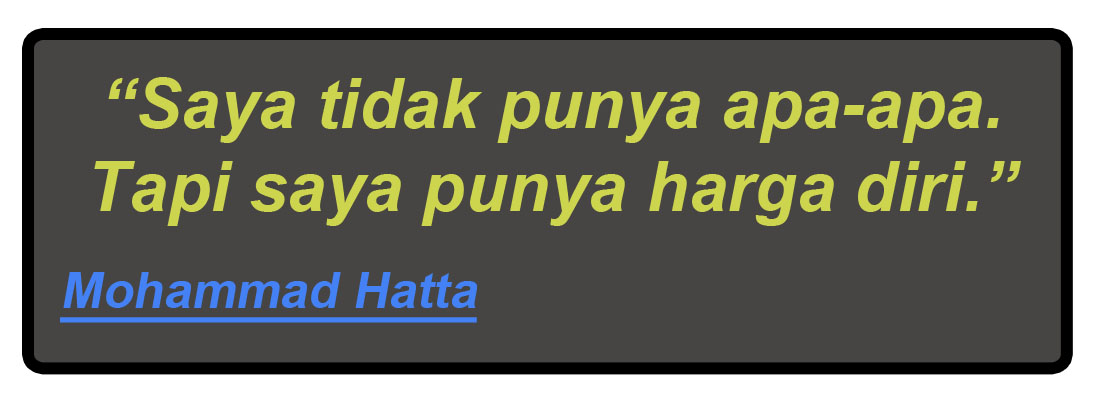 Koperasi: Menyalakan Cahaya untuk
Semua
Koperasi: Menyalakan Cahaya untuk
Semua
Hatta
percaya, koperasi adalah cara rakyat menyalakan lampu kehidupannya sendiri.
Koperasi bukan sekadar tempat berjualan atau meminjam uang. Ia adalah ruang
bersama, di mana setiap orang yang masuk menjadi pemilik sekaligus penentu
arah. Di mata Hatta, koperasi adalah perwujudan nyata dari kemerdekaan ekonomi:
rakyat tidak menunggu bantuan, tidak tunduk pada tengkulak, dan tidak
tergantung pada kemurahan hati segelintir orang.
Seperti
dirinya yang memilih hidup tanpa menggadaikan harga diri, Hatta ingin rakyat
kecil juga mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dengan koperasi, cahaya di
rumah-rumah rakyat tak akan padam hanya karena tak mampu membayar. Sebab, yang
dinyalakan bukan hanya lampu listrik, tapi juga semangat, kemandirian, dan
martabat.
Bung Hatta mencintai koperasi bukan karena itu
alat ekonomi, tapi karena itu cerminan dari nilai yang beliau pegang teguh:
gotong royong, keadilan, dan martabat manusia. Baginya koperasi
itu bukan perusahaan, tapi gerakan moral. Koperasi itu cara
untuk mengangkat yang kecil tanpa harus menindas yang besar. Koperasi itu ruang
buat semua orang tumbuh bersama, bukan saling sikut demi keuntungan pribadi.
Beliau menyampaikan bahwa ia lebih memilih koperasi berkembang daripada seribu orang
kaya baru. Karena yang beliau ingin lihat bukan orang sukses sendirian,
tapi masyarakat yang naik kelas bersama-sama.
Refleksi Kecil Buat Kita
Hari
ini, koperasi kadang kehilangan ruhnya. Ada yang sekadar formalitas. Ada yang
dikelola layaknya bisnis biasa — bahkan kadang malah jadi alat segelintir orang
buat menyedot keuntungan.
Padahal,
kalau kita mau jujur… apa yang Bung Hatta ajarkan itu justru paling
relevan hari ini.
Saat
semua serba instan, Bung Hatta mengajari kita tentang kesabaran dan
proses.
Saat
semua orang ingin cepat kaya, dia justru mengajarkan hidup cukup dan
jujur.
Saat kekuasaan
jadi panggung, dia justru memilih diam dan menulis.
Dan
koperasi, kalau mau bertahan… harus kembali ke nilai itu. Ke akar. Ke hati.
Kita
mengenang Bung Hatta bukan hanya sebagai proklamator atau Bapak Koperasi. Tapi
juga sebagai manusia langka yang ajarannya tak pernah berhenti relevan: tentang
integritas, kesederhanaan, dan cinta pada bangsa tanpa pamrih.
Selamat ulang tahun, Bung Hatta..

> 📝 Catatan:
Kisah tentang anak-anak Bung Hatta baru membelikan sepatu Bally
setelah beliau wafat, merupakan kisah populer yang banyak beredar dari mulut ke
mulut di masyarakat. Meskipun tidak selalu terdokumentasikan secara resmi dalam
sumber sejarah primer, cerita ini tetap hidup dan dipercaya banyak orang
sebagai cerminan kesederhanaan dan integritas Bung Hatta.
·
